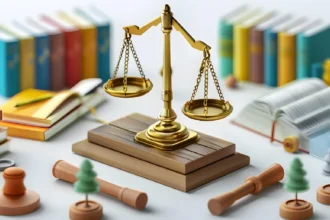Dalam sistem hukum acara pidana, dikenal dua asas yang menjadi dasar terbentuknya proses peradilan yaitu asas akusator (accusatoir) dan asas inkisitor (inquisitoir). Keduanya merepresentasikan dua paradigma besar dalam penegakan hukum antara perlindungan terhadap hak asasi tersangka dan pencarian kebenaran materiil oleh negara.
Artikel ini akan membahas secara komprehensif perbedaan antara asas akusator dan inkisitor, serta penerapannya dalam sistem hukum Indonesia.
Asas Akusator: Perlindungan terhadap Hak Tersangka
Asas akusator menempatkan tersangka atau terdakwa sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak penuh dalam proses peradilan. Dalam sistem ini, pengadilan bersifat terbuka, seimbang, dan menjunjung prinsip fair trial. Hakim berperan netral, sementara jaksa dan pembela memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.
Penerapan asas ini di Indonesia tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terutama pada Pasal 50 hingga Pasal 68, yang mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, hak atas bantuan juru bahasa, serta hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri.
Selain itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, atau ditahan wajib diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang dikenal sebagai asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Asas ini sejalan dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, menegaskan hak setiap orang untuk mendapatkan peradilan yang adil (fair and public hearing).
Asas Inkisitor: Dominasi Negara dalam Proses Peradilan
Berbeda dengan sistem akusator, asas inkisitor berasal dari sistem civil law Eropa Kontinental, yang menekankan pencarian kebenaran materiil oleh negara.
Dalam sistem tersebut, hakim atau penyidik berperan aktif dalam mencari, menemukan, dan menilai bukti. Tersangka tidak sepenuhnya diperlakukan sebagai subjek hukum, melainkan lebih sebagai objek penyelidikan, di mana hak pembelaan cenderung terbatas.
Baca Juga: Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Ketika Hakim Ragu
Dalam sejarah hukum Indonesia, corak inkisitorial tampak pada sistem hukum kolonial yang diatur dalam Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan Reglement op de Strafvordering (RvS). Pada masa itu, pengakuan tersangka dianggap sebagai bukti utama, bahkan sering diperoleh melalui cara-cara yang kini dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia.
Menurut Andi Hamzah (1987) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, sistem inkisitor berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan karena posisi negara terlalu dominan. KUHAP 1981 kemudian hadir untuk mengoreksi kecenderungan inkisitorial ini, dan menggeser sistem peradilan Indonesia ke arah yang lebih akusatoris.
Namun, sisa-sisa sistem inkisitor masih dapat ditemukan dalam tahap penyidikan. Pada tahap ini, penyidik (polisi atau jaksa) memang diberikan peran aktif untuk menggali keterangan dan mengumpulkan bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka.
Perbandingan dan Penerapan dalam Sistem Hukum Indonesia
Sistem hukum Indonesia saat ini menganut model campuran antara asas akusator dan inkisitor.
Tahap penyidikan bersifat inkisitorial, di mana penyidik aktif mencari bukti.
Menurut Andi Hamzah (1987) dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, penyidikan memang bersifat inkisitorial karena negara berwenang mencari kebenaran materiil, namun tetap harus dibatasi agar tidak melanggar hak-hak dasar tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 50–68 KUHAP diantaranya: memperoleh penasihat hukum sejak awal pemeriksaan (Pasal 54 KUHAP), menolak menjawab pertanyaan yang dapat memberatkan dirinya (Pasal 175 KUHAP), dan tidak disiksa atau ditekan dalam proses penyidikan (Pasal 117 KUHAP).
- Sedangkan tahap persidangan bersifat akusatorial, di mana jaksa dan penasihat hukum memiliki posisi yang seimbang di hadapan hakim yang netral.
M. Yahya Harahap (2009) dalam Pembahasan dan Penerapan KUHAP menjelaskan bahwa sistem peradilan kita bersifat akusatorial karena “hakim bukan lagi pengusut kebenaran, tetapi penilai keabsahan alat bukti yang diajukan secara berimbang antara penuntut umum dan penasihat hukum.” Artinya, hakim tidak boleh menggantikan peran jaksa dalam membuktikan, atau peran advokat dalam membela. Inilah ciri utama sistem akusator: pengadilan terbuka, keseimbangan posisi, dan perlindungan hak pembelaan.
Pandangan ini sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap (2009) dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, yang menegaskan bahwa “KUHAP berupaya membangun sistem peradilan pidana yang menjamin hak-hak individu tanpa mengorbankan tujuan hukum untuk menemukan kebenaran materiil.”
Baca Juga: Ini 9 Macam Asas Hukum Acara Pidana
Kesimpulan
Pemahaman mendalam terhadap asas akusator dan inkisitor bukan hanya soal teori dalam hukum acara, tetapi merupakan fondasi strategis bagi setiap advokat dalam membela kepentingan kliennya. Kedua asas ini menggambarkan keseimbangan yang harus dijaga antara kekuasaan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak-hak individu agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.